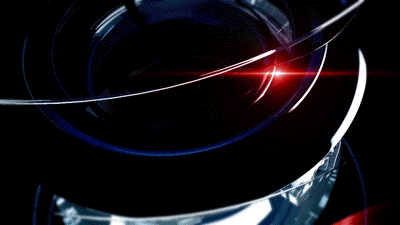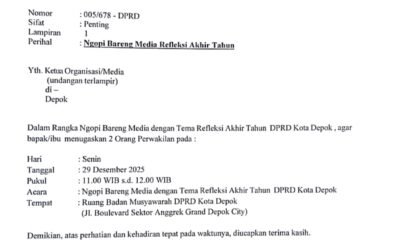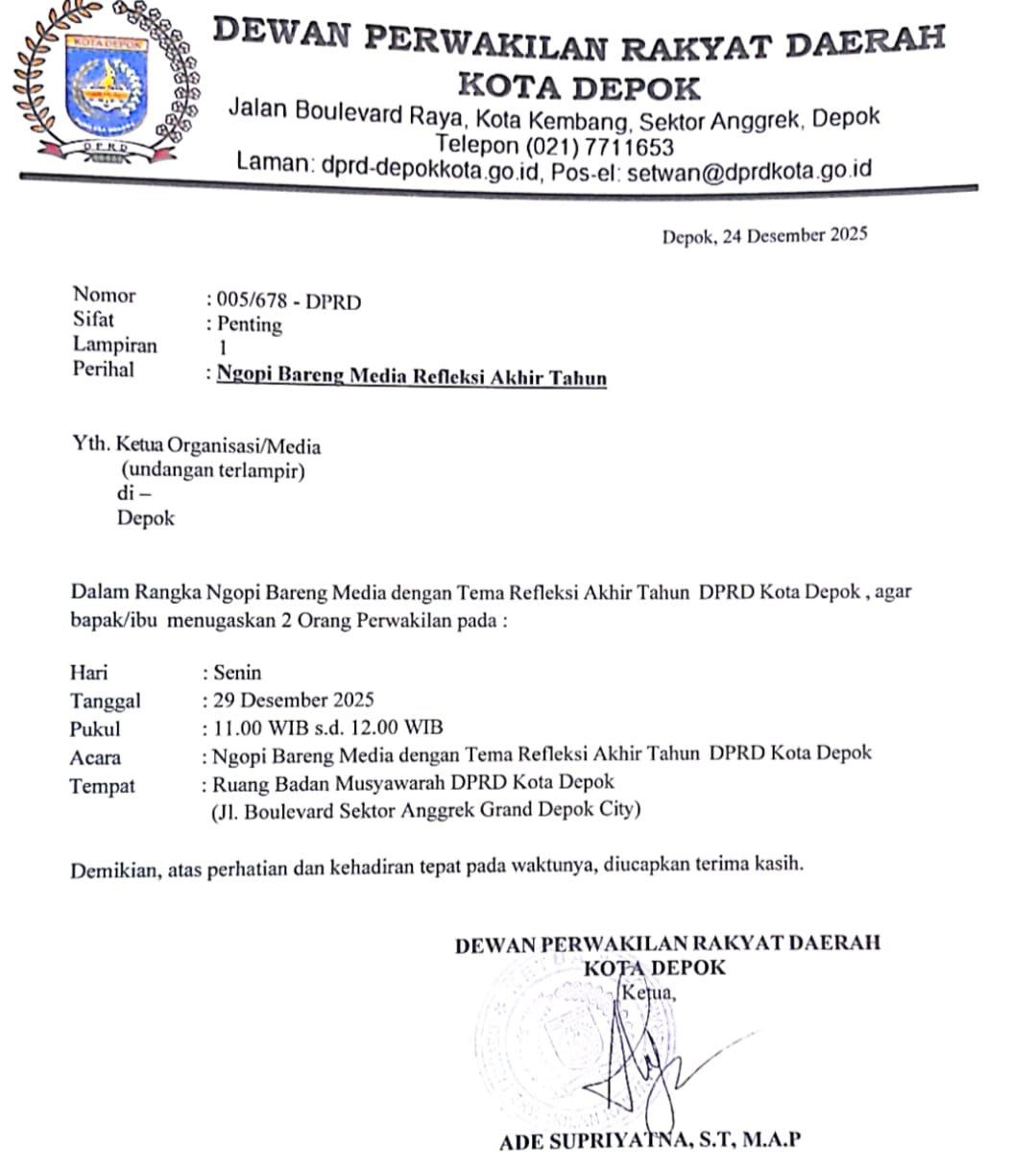Kebebasan Beragama dan Persekusi Terpinggirkan, Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Disorot

Jakarta, NewsGBN.com – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD, Jumat (15/8/2025), yang sarat janji ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan yang baik dan bersih, dan pertahanan nasional, sumber daya alam, serakahnomic, menuai kritik keras. Bukan karena isinya yang penuh optimisme, melainkan karena diamnya Presiden terhadap isu hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan maraknya persekusi terhadap kelompok minoritas.
Bagi sejumlah aktivis, akademisi, dan pemerhati hukum dan HAM, absennya isu fundamental ini justru memperlihatkan arah pemerintahan yang hanya menekankan pembangunan fisik, tetapi abai terhadap persoalan konstitusional warga negara.
“Pidato Presiden itu penuh kata-kata besar soal masa depan bangsa, tapi justru mengabaikan masalah paling mendasar, hak setiap orang untuk beribadah dengan tenang dan bebas dari persekusi. Diamnya Presiden dalam isu ini sangat memprihatinkan,” ujar Hotman Samosir, S.H., D.Com, pendiri PILAR sekaligus aktivis sosial, politik, dan hukum, Jumat (15/8).
Aktivis Hotman menegaskan, hak kebebasan beragama bukanlah isu kaleng-kaleng. Konstitusi sudah dengan tegas mengaturnya. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sementara Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
“Bagaimana mungkin Presiden berpidato tentang welfare state dan persatuan bangsa tapi melupakan salah satu fondasi konstitusional persatuan itu sendiri?” kritik Hotman Samosir.
Menurutnya, negara justru semakin kehilangan arah ketika masalah kebebasan beragama dan menjalankan agama hanya dianggap sebagai isu teknis yang diserahkan ke pemerintah daerah. Faktanya, diskriminasi dan pelanggaran paling sering justru lahir di tingkat lokal, ketika izin rumah ibadah dipersulit/ditolak, kegiatan ibadah dibubarkan, persekusi, perusakan, hingga aparat tunduk dan jadi penonton pada tekanan kelompok intoleran.
Hotman mencontohkan kasus penolakan pembangunan Gereja di Depok, perusakan dan persekusi atribut keagamaan di Cidahu (Sukabumi), pembubaran kegiatan umat minoritas di Padang, penolakan pembangunan Masjid di Maybrat, larangan peribadatan di Vihara Cengkareng Barat, hingga ancaman intoleransi di sejumlah kota besar dan daerah lain.
“Kasus-kasus ini nyata, berulang, dan belum pernah diselesaikan secara adil dan tegas. Kalau Presiden tidak bicara di forum setinggi Sidang Tahunan MPR, lalu kapan negara mau menunjukkan keberpihakan pada konstitusi?” tegasnya.
Lebih jauh, Hotman mengingatkan bahwa diamnya Presiden dalam isu kebebasan beragama memberi sinyal berbahaya, intoleransi akan dianggap sebagai hal lumrah. Padahal, Indonesia terus menjadi sorotan dunia dalam laporan kebebasan beragama internasional.
“Kita bisa kehilangan muka di dunia internasional, dan lebih parah lagi, kehilangan kepercayaan rakyat yang minoritas bahwa negara ini ‘melindungi’ mereka,” tambahnya.
Dari sisi hukum, ia menyoroti regulasi diskriminatif yang masih berlaku, khususnya SKB 2 Menteri 2006 tentang pendirian rumah ibadah, yang sering menjadi alat pembatasan.
“Regulasi ini bertentangan dengan semangat konstitusi, tapi anehnya tidak ada kemauan politik dari Presiden dan elite untuk membicarakan reformasi hukum. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi lemahnya komitmen HAM dalam pemerintahannya,” kata Hotman.
Selain itu, ia juga menyinggung peran oknum aparat keamanan yang kerap bertindak pasif atau bahkan berpihak pada kelompok intoleran. “Kalau Presiden ingin menegakkan konstitusi dan peduli terhadap HAM, instruksi tegas harus diberikan ke aparat agar melindungi kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, bukan sekadar menjaga ketertiban formal. Negara tidak boleh kalah dari kelompok tekanan,” ujarnya.
Hotman mengusulkan tiga langkah konkret yang seharusnya dilakukan Presiden dan elite politik: Pertama, perintah politik jelas untuk aparat melindungi minoritas; kedua, reformasi regulasi diskriminatif seperti SKB 2006; ketiga, pendidikan publik berkelanjutan tentang toleransi dan kebhinnekaan. “Tanpa tiga langkah ini, intoleransi dan persekusi hanya akan terus menjadi lingkaran setan,” tegasnya.
Dengan absennya isu hak asasi manusia, terutama jaminan kebebasan beragama atau kepercayaan dan mendirikan tempat ibadah dalam pidato perdana kenegaraan, publik kini menunggu apakah Presiden akan memperbaiki kelalaiannya melalui kebijakan nyata, atau membiarkan intoleransi dan persekusi terus menjadi wajah buram demokrasi Indonesia.
“Kalau Presiden Prabowo tidak segera membuktikan komitmen pada jaminan kebebasan beragama/kepercayaan dan mendirikan tempat ibadah, sejarah akan mencatat pemerintahannya sebagai periode yang menormalisasi intoleransi dan persekusi. Pidato kemarin sangat disayangkan, terutama minoritas dan pegiat HAM, dan rakyat berhak mengingatnya.” pungkas Hotman Samosir sambil mengingatkan. (Red)